Menggali Epistemologi Khaldunian dalam Kitab al-Muqaddimah
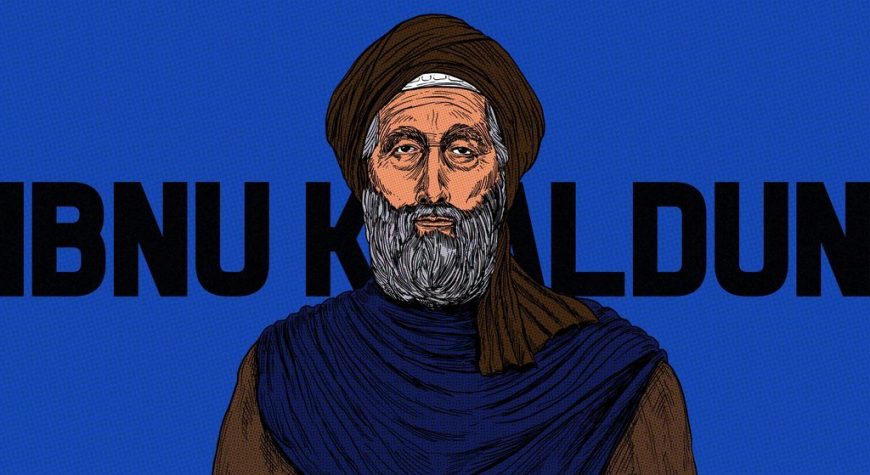
Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun sebagai sejenis karya mengenai epistemologi bukanlah barang baru di dunia Islam. Penulisan tentang epistemologi merupakan suatu hal yang biasa terjadi di kalangan para pemikir Islam pada abad pertengahan. Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun sebagai karya pengantar epistemologi yang mengulas suatu objek pengetahuan tertentu dengan pijakan epistemik dan metodologi tertentu bukanlah sesuatu yang unik.
Artinya, sebelum al-Muqaddimah ini, sudah banyak karya-karya besar yang memfokuskan perhatiannya pada apa itu dasar-dasar pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan apa saja yang dianggap valid, instrument pengetahuan apa yang sekiranya bisa membawa kita kepada pemahaman yang utuh tentang objek pengetahuan. Ringkasnya, para pemikir Islam sudah banyak yang berkecimpung dalam dunia epistemologi.
Jadi sejak awal perkembangannya, kebudayaan Islam sudah mengenal proyek pembangunan epistemology dalam berbagai cabang pengetahuan. Proyek pembangunan epistemologi ini dimulai dari masa kodifikasi pengetahuan pada abad kedua hijriah. Para ahli nahwu, dari semenjak awal perkembangannya, misalnya, membangun basis-basis pengetahuan tentang bahasa Arab berikut dengan oto-kritik terhadap hasil pengamatan berbagai aspek gramatikal bahasa Arab itu sendiri.
Hasil dari proyek ini ialah munculnya karya-karya monumental dalam filsafat nahwu seperti al-Ain karya Khalil bin Ahmad al-Farahidi, al-Kitab karya Imam Sibawaih atau al-Khasa’ish karya Ibnu Jinni. Karya-karya ini memiliki nilai epistemologi yang tinggi dan kajian linguistik yang luar biasa, bahkan mungkin melampaui tradisi penulisan tata bahasa Sansakerta oleh Panini di beberapa abad sebelumnya dan strukturalisme modern oleh Saussure dan Leonard Bloomfield di awal abad kedua puluh ini.
Para ulama Usul Fikih juga berusaha membangun metode induktif dalam kajian-kajian epistemiknya, dan barangkali usaha ini baru pertama kali diterapkan dalam pengamatan hukum sepanjang sejarah pengetahuan manusia.
Sedangkan kaum filosof Islam, meski karya-karya mereka tentang logika masih dalam bayang-bayang pengaruh Aristoteles, berusaha untuk melampaui kosmologi peripatetik tradisional, baik dalam ranah klasifikasi pengetahuan maupun dalam ranah mengkritik basis-basis pengetahuan. Ikhwan as-Shofa, misalnya, melalui risalah-risalah yang mereka tuliskan juga memiliki proyek pembangunan epistemologi yang unik. Usaha yang mereka lakukan ini cukup menyeluruh dan komperehensif.
Ini bisa kita lihat keluasan jangkauan pengetahuan mereka dalam risalah-risalah pengetahuan yang mereka tuliskan. Ikhwan as-Shofa dalam karya-karyanya ini berusaha mengkombinasikan filsafat, ilmu pengetahuan dan agama agar tercapai keselarasan antara rasio dan wahyu berbasis pada asas epistemologi yang kokoh. Epistemologi yang dibangun oleh Ikhwan as-Shofa ini berbasis pada upaya merasionalisasi ilmu-ilmu yang irasional agar bisa hidup berdampingan dan tanpa konflik yang cukup berarti dengan ilmu-ilmu yang rasional.
Perhatian terhadap epistemologi dalam kebudayaan Arab-Islam ini sebenarnya didorong oleh konflik epistemik antar berbagai aliran pengetahuan dalam Islam, baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, nahwu, ilmu kalam, maupun dalam bidang filsafat.
Dalam konflik pengetahuan ini, kita dihadapkan pada fenomena kemunculan berbagai macam mazhab dan aliran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan di saat yang bersamaan pula saling bertubrukan dan berbenturan. Semua itu digerakkan oleh perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi yang dilakukan secara intense. Sebab itu, perdebatan itu sendiri dalam kebudayaan Arab Islam ini menjadi ilmu dan seni tersendiri yang bisa dipelajari.
Agar diskusi dan perdebatan berlangsung secara lancar, para pemikir Islam di masa itu menulis karya-karya mereka dengan susunan yang logis dan runut berbasis pada metodologi yang jelas. Biasanya metodologi ini dijelaskan di awal dalam bentuk pendahuluan (al-madkhal wal muqaddimat).
Karya-karya induk dalam bidang fikih, nahwu, kalam, filsafat dan seterusnya biasanya dimulai dengan pendahuluan tentang kerangka pengetahuan yang akan digunakan. Pendahuluan ini meliputi bahasan soal prinsip-prinsip, metode-metode, persoalan-persoalan yang akan didiskusikan. Ini misalnya kitab ar-Risalah yang ditulis Imam as-Syafi’i sebagai pengantar untuk kitab al-Umm. Kitab at-Tamhid fi Ilmil Kalam karya al-Baqillani, Ushuluddin karya Abdul Qahir al-Baghdadi, as-Syamil karya al-Juwaini semuanya ialah karya dalam bidang ilmu kalam yang pembahasannya selalu diawali dengan hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi.
Biasanya pendahuluan yang berisi bahasan epistemologi ini mengulas tentang pengetahuan, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, ilmu-ilmunya, metode-metodenya dan seterusnya…yang pada tahap selanjutnya, si pemikir langsung masuk ke persoalan inti yang hendak diulasnya.
Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ini merupakan kelanjutan dari model penulisan epistemologi dalam kebudayaan Islam pada umumnya. Namun, dengan titik tekan berbeda. Ulama asy’ariyyah misalnya menulis pengantar epistemologis dalam karya-karya mereka tentang kalam yang meliputi aturan-aturan, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip pengetahuan yang bisa menjadi basis legitimasi bagi keabsahan keyakinan al-Asy’ariyyah.
Jadi epistemologi digunakan oleh al-Asyariyyah untuk melegitimasi keabsahan keyakinan aliran ini. Muktazilah juga melakukan hal yang sama. Secara ringkasnya, epistemologi dalam aliran Muktazilah dan Asyariyyah ditulis untuk kepentingan ideologi aliran.
Ibnu Khaldun memiliki keunikan tersendiri. Jika Asy’ariyyah menuliskan perangkat epistemologi untuk mendukung madzhabnya dari serangan-serangan lawan dalam berbagai karya mereka, Ibnu Khaldun justru lain. Ibnu Khaldun, ketika menulis epistemologi dalam al-Muqaddimah, berangkat dari ambisi untuk membangun suatu kerangka pengetahuan tersendiri, kerangka pengetahuan yang disebutnya sebagai ilmu umran.
Sampai di sini, kita melihat bahwa Ibnu Khaldun berambisi untuk memberikan pondasi bagi ilmu baru yang dengannya sejarah dapat ditransformasikan dari yang sekedar deskripsi naratif belaka ke level ilmu pengetahuan tersendiri.
Rasio dan Jiwa dalam Epistemologi Khaldunian
Sejak awal, al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menyajikan pemaparan epistemologi yang cukup unik dan mendalam. Paling tidak, ketika membaca al-Muqaddimah ini, kesan yang akan kita dapatkan ialah bahwa Ibnu Khaldun seolah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
Pertama, bagaimana kita dapat membangun suatu ilmu pengetahuan dengan berkaca dari sejarah masa silam?
Kedua, bagaimana kita bisa memperoleh perspektif baru dalam melihat peristiwa-peristiwa di masa lampau?
Ketiga, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang ilmiah berbasis pada prinsip bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu akan selalu tunduk terhadap hukum-hukum tertentu?
Keempat, bagaimana kita bisa memberikan status kenalaran terhadap peristiwa-peristiwa kesejarahan?
Kelima, bagaimana kita bisa menemukan dan memahami elan vital atau daya hidup yang menggerakan aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya?
Pertanyaan-pertanyaan ambisius ini sebenarnya sering muncul dalam dunia pemikiran modern abad ke-20. Namun pertanyaannya ialah bagaimana mungkin Ibnu Khaldun yang hidup di era kemunduran kebudayaan Islam bisa sampai mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu dalam ini? Bagaimana beliau yakin akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini?
Kualitas pertanyaan dan jawaban memang tidak melulu berkaitan dengan ambisi si subjek penahu. Semua itu terkadang berangkat dari perangkat pengetahuan atau perangkat epistemologi yang digunakan. Tak ayal, perangkat epistemologi yang digunakan Ibnu Khaldun sangat berbeda jauh dengan perangkat epistemologi yang kita gunakan saat ini. Perangkat epistemologi Ibnu Khaldun lebih luas dan menyeluruh dari yang kita miliki.
Sampai di sini, berangkat dari perangkat epistemologi yang kita gunakan, pertanyaan-pertanyaan ambisius di atas jelas tidaklah menemukan relevansinya di masa kita ini. Kendati demikian, jika kita lihat pertanyaan-pertanyaan di atas melalui perangkat epistemologi yang digunakan Ibnu Khaldun sendiri, tentu bisa bisa dibenarkan dan tentu sangat relevan.
Perangkat epistemologi yang kita miliki ialah perangkat epistemologi yang hanya memiliki satu dimensi, yakni dimensi yang batasan-batasannya sangat ditentukan oleh pengalaman dan silogisme dan semua prinsip-prinsip teoretis yang dibentuk oleh pengalaman dan silogisme. Batasan dan prinsip teoretis yang dibentuk oleh pengalaman dan silogisme membentuk apa yang sekarang kita sebut pemikiran ilmiah. Sedangkan perangkat epistemologi yang digunakan oleh Ibnu Khaldun memiliki dua dimensi:
Pertama, dimensi yang batasan-batasannya ditentukan oleh rasio. Rasio di sini dimaknai sebagai daya pikir berbasis pengalaman dan pencerapan panca indera. Rasio ini cara kerjanya ialah intensi ke luar subjek yang biasanya melihat kronologi tiap peristiwa untuk mengetahui sebab akibatnya atau hukum kausalitasnya. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, rasio seperti ini namanya ialah rasio empiris (al-aql at-tajribi).
Kedua, dimensi yang batasan-batasannya ditentukan oleh jiwa. Jiwa menurut Ibnu Khaldun ialah “entitas ruhani yang memiliki potensi untuk terlepas dari pengaruh naluri kemanusiaan sehingga bisa masuk ke alam malaikat dan menjadi seperti malaikat dan melalui jiwa ini, si subjek dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan ghaib”.
Sampai di sini, melalui perangkat epistemologi yang berbasis pada dua dimensi ini: dimensi rasio dan dimensi jiwa, Ibnu Khaldun dengan sendirinya dapat menafsirkan lebih jauh dan memberikan penjelasan lebih rinci tentang semua fenomena kesejarahan, fenomena kehidupan manusia secara keseluruhan, baik fenomena spritiual maupun fenomena material.
Dengan dua perangkat epistemologi ini, semua fenomena yang tidak bisa ditafsirkan oleh rasio dapat ditafsirkan oleh jiwa. Jika ada objek pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh rasio, maka ia bisa didekati dengan jiwa. Misalnya surga, neraka, akhirat dan seterusnya merupakan wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh rasio namun bisa direngkuh oleh jiwa. Dan yang lebih mudahnya lagi, dualisme yang ada pada tataran epistemologi ini sangat bersesuaian dengan dualisme yang ada pada tataran ontologi: alam materi dan alam ruhani.
Rasio hanya bisa digunakan sebagai perangkat epistemologis untuk memahami hal-hal yang ada di alam materi sedangkan jiwa hanya bisa digunakan untuk memahami hal-hal yang ada di alam spiritual. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh rasio bisa dijangkau oleh jiwa. Meski jiwa bisa menjangkau yang tak terjangkau rasio namun perananya hanya bersifat subjektif dan tidak bisa disampaikan dan diajarkan ke orang lain. Sebut saja, pengetahuan hasil olahan jiwa tidak bisa diobjektifikasi.
Rasio dan jiwa memang merupakan perangkat epistemologi yang menjadi basis pondasional bagi pemikiran Yunani Kuno dan pemikiran abad pertengahan. Namun demikian, berbeda dari pemikir Yunani dan pemikir abad pertengahan, Ibnu Khaldun malah memberikan fungsi baru terhadap peranan rasio dan jiwa ini dalam menafsirkan semua fenomena material dan fenomena spiritual. Bahkan bisa dikatakan, Ibnu Khaldun melampaui pemikiran Yunani dan abad pertengahan soal rasio dan jiwa dalam pemerolehan pengetahuan.
Dengan dua perangkat epistemologis ini, jiwa dan rasio, Ibnu Khaldun bahkan mengkritik berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang sampai ke masanya. Ulasan-ulasannya tentang berbagai pengetahuan yang berkembang dalam kebudayaan Arab Islam berbasis pada dua perangkat epistemologis ini, dengan sendirinya, membentuk epistemologi yang khas khaldunian.
Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana Ibnu Khaldun menggunakan rasio dan jiwa pada tataran ontologi dan epistemologi.

Peneliti Dialektika Institute for Culture, Religion and Democracy

